ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL
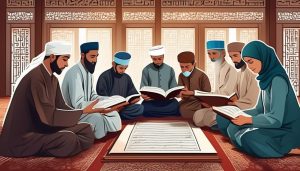
Oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LC., MEI.
Islam dan kearifan lokal merupakan dua entitas yang saling berinteraksi dalam membentuk peradaban masyarakat di berbagai belahan dunia, terutama di Indonesia. Kearifan lokal yang terbentuk dari adat-istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun sering kali memiliki hubungan harmonis dengan ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup mayoritas masyarakat. Hubungan ini menghasilkan interaksi yang dinamis, di mana Islam tidak hanya diterima sebagai ajaran agama, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas budaya dan tradisi lokal.
Sebagai agama yang bersifat universal, Islam membawa nilai-nilai yang bersifat transendental. Namun, nilai-nilai ini tidak serta-merta menghapus budaya setempat, melainkan Islam justru memberikan ruang bagi adaptasi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam syariah. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama yang dapat berkembang dengan damai di berbagai tempat dengan konteks budaya yang berbeda-beda, termasuk di Indonesia.
Sebagai contoh, penyebaran Islam di Nusantara melalui pendekatan yang kultural, seperti yang dilakukan oleh Wali Songo, adalah bukti bagaimana Islam dapat disebarkan tanpa merusak tatanan sosial yang sudah ada, melainkan justru memperkaya nilai-nilai lokal yang sudah tumbuh di masyarakat. Tradisi-tradisi seperti slametan, maulid, dan syawalan menjadi cerminan bagaimana nilai-nilai Islam terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang kaya akan kearifan lokal.
Pembahasan mengenai Islam dan kearifan lokal penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana interaksi ini dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam sekaligus menjaga keberagaman budaya yang ada di dunia. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi landasan bagi upaya menciptakan harmoni antara modernisasi, Islam, dan budaya lokal dalam menghadapi tantangan globalisasi.
Kajian ini akan mengurai lebih lanjut konsep kearifan lokal, bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya setempat, serta bagaimana kedua hal ini berkontribusi terhadap pembangunan peradaban yang harmonis dan berkelanjutan. Penekanan akan diberikan pada prinsip-prinsip dasar Islam, seperti tauhid dan akhlak, serta pada praktik-praktik kearifan lokal yang tidak hanya relevan dalam kehidupan sosial, tetapi juga mendukung perkembangan dakwah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Penjelasan terperinci mengenai “Islam dan Kearifan Lokal’ yang merujuk kepada Alquran, hadis, serta pandangan ulama, menuntut kajian mendalam yang mencakup dalil-dalil agama dan pandangan para sarjana Islam dalam konteks budaya lokal. Berikut adalah uraian yang merujuk kepada sumber-sumber primer dalam Islam:
1. Pengertian Kearifan Lokal.
Kearifan lokal dapat dipahami sebagai nilai-nilai, norma, atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat berdasarkan tradisi dan budaya turun-temurun. Dalam Islam, segala bentuk budaya dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam dapat diterima dan diadopsi.
Dalam Alquran, konsep ini berhubungan dengan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah) dan menjaga harmoni sosial. Allah SWT berfirman:
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
“Dan Kami telah menciptakan kamu dalam berbagai bangsa dan suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” (QS. Al-Hujurat: 13)
Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya, suku, dan bangsa adalah sunnatullah yang harus dihargai. Kearifan lokal dapat menjadi sarana untuk memperkuat ukhuwah selama nilai-nilainya sejalan dengan ajaran Islam.
2. Islam dan Budaya Lokal.
Islam memiliki pendekatan yang fleksibel dalam menghadapi budaya lokal. Selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariah, maka Islam membiarkan bahkan memodifikasinya. Nabi Muhammad SAW sendiri menggunakan beberapa tradisi lokal Arab dalam dakwahnya selama tradisi tersebut tidak mengandung kemusyrikan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda:
إنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق
“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad, no. 8952)
Penerapan budaya lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti tradisi slametan, maulid, dan syawalan di Indonesia merupakan bentuk adaptasi budaya yang tetap mempertahankan nilai akhlak Islami.
3. Adaptasi Nilai-nilai Islam dalam Kearifan Lokal.
Proses adaptasi Islam terhadap budaya lokal dikenal sebagai Islamisasi. Dalam hal ini, budaya lokal disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam sehingga tidak bertentangan dengan syariah. Contohnya adalah penggunaan bahasa lokal dalam dakwah, seni, dan arsitektur masjid. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin menyatakan pentingnya menyesuaikan metode dakwah dengan kondisi masyarakat lokal:
النَّظَرُ إلَى حَالِ الْمَأْمُورِينَ مِنْ طُرُقِ دَعْوَتِهِمْ
“Memperhatikan keadaan orang-orang yang diperintahkan merupakan bagian dari metode dakwah.” (Ihya’ Ulumuddin, Juz 1, hal. 23)
4. Prinsip Tawhid dan Keberagaman Budaya.
Dalam Islam, prinsip Tauhid menjadi landasan utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam menghadapi budaya. Selama budaya tidak bertentangan dengan Tauhid dan tidak mengandung kemusyrikan, maka Islam mendorong umatnya untuk menghargai budaya setempat. Allah SWT berfirman:
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
“Katakanlah: Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah.” (QS. Al-Kafirun: 1-3)
Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga keyakinan Tauhid dalam menghadapi budaya yang mungkin bertentangan dengan prinsip Islam.
5. Kearifan Lokal sebagai Wujud Akhlak Islam.
Islam menekankan pentingnya akhlak yang mulia. Banyak nilai dalam kearifan lokal, seperti “gotong-royong” dan kepedulian sosial, sejalan dengan ajaran Islam tentang akhlak yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
“Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung persaudaraan dan gotong-royong sangat sesuai dengan ajaran Islam ini.
6. Kontribusi Kearifan Lokal terhadap Dakwah Islam.
Pendekatan dakwah yang mengadopsi kearifan lokal terbukti efektif dalam menyebarkan Islam di berbagai wilayah. Wali Songo, sebagai contoh, menggunakan budaya Jawa dalam dakwah mereka. Imam Asy-Syafi’i dalam kitabnya Ar-Risalah menekankan pentingnya memahami konteks lokal dalam penyebaran agama:
يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِمَا فِيهِ وِفْقًا لِحَالِ النَّاسِ وَقِيَاسًا عَلَى مَعْرُوفِهِمْ
“Menafsirkan Alquran sesuai dengan keadaan masyarakat dan mengukur berdasarkan yang dikenal oleh mereka’ (Ar-Risalah, hal. 124)
7. Islam, Kearifan Lokal, dan Pembangunan Masyarakat.
Kearifan lokal memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Nilai-nilai Islam seperti keadilan (al-‘adalah) dan kepedulian terhadap lingkungan sejalan dengan banyak kearifan lokal yang menekankan pelestarian alam. Allah SWT berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِه
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki.”* (QS. Al-A’raf: 56).
Budaya lokal yang menjaga keseimbangan alam dan mendukung perekonomian kerakyatan sangat sesuai dengan ajaran Islam.
8. Tantangan dan Peluang Integrasi Islam dan Kearifan Lokal.
Dalam menghadapi tantangan modernisasi, kearifan lokal dapat membantu menjaga identitas budaya dan agama. Islam, dengan fleksibilitasnya, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip utamanya. Namun, modernisasi juga menghadirkan tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara budaya lokal dan prinsip-prinsip syariah. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya al-wasatiyyah (moderasi) dalam menghadapi budaya modern:
فَإِنَّ التَّوَسُّطَ فِي الأُمُورِ هُوَ خَيْرُ سَبِيلٍ
“Sesungguhnya sikap moderat dalam segala hal adalah jalan yang terbaik.” (Al-Fiqh Al-Wasatiyyah, hal. 48)
Interaksi antara Islam dan kearifan lokal merupakan wujud dari kemampuan Islam dalam beradaptasi dengan berbagai budaya yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Kearifan lokal yang dihasilkan dari adat, tradisi, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun tidak hanya menjadi identitas budaya suatu masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat harmoni sosial dan kehidupan spiritual.
Dalam proses adaptasi ini, Islam tidak menolak budaya lokal secara keseluruhan, tetapi menyaring unsur-unsur yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah seperti tauhid, akhlak, dan keadilan. Tradisi-tradisi lokal seperti slametan, maulid, dan syawalan adalah contoh bagaimana budaya lokal dapat berintegrasi dengan ajaran Islam tanpa mengorbankan nilai-nilai inti agama.
Pembahasan mengenai Islam dan kearifan lokal menegaskan bahwa Islam, sebagai agama yang fleksibel dan inklusif, mampu bersanding dengan kearifan lokal tanpa harus kehilangan esensinya. Integrasi ini tidak hanya menguntungkan bagi perkembangan agama, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat yang majemuk.
Dalam konteks modernisasi dan globalisasi, menjaga keseimbangan antara Islam dan kearifan lokal menjadi sangat penting. Globalisasi dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal yang telah lama menjadi bagian dari identitas masyarakat, namun dengan prinsip-prinsip Islam yang kuat, kearifan lokal dapat tetap terpelihara dan bahkan berfungsi sebagai alat untuk memperkaya dinamika kehidupan beragama dan sosial.
Pada akhirnya, kajian tentang Islam dan kearifan lokal menunjukkan bahwa keberagaman budaya bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk menciptakan harmoni antara tradisi dan agama. Dengan
pemahaman yang mendalam, Islam dan kearifan lokal dapat saling memperkaya dan berkontribusi terhadap pembentukan peradaban yang berkelanjutan, baik dari sisi agama, budaya, maupun sosial.
Daftar Pustaka :
1. Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya’ Ulumuddin. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
2. Asy-Syafi’i, Muhammad ibn Idris. *Ar-Risalah. Cairo: Maktabah al-Khanji, 1940.
3. Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Fiqh Al-Wasatiyyah wa Tajdiduh. Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1998.
4. Rahardjo, Dawam. Islam dan Transformasi Sosial. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999.
5. Abdurrahman, Moeslim. *Islam Transformatif: Islam dan Pergeseran Struktur Sosial. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
6. Zainuddin, Zulkifli. Islam dan Kearifan Lokal: Studi Hubungan Islam dan Budaya Lokal di Indonesia. Yogyakarta: LKiS, 2010.
7. Geertz, Clifford. The Religion of Java. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
8. Munir, Ahmad. “Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kearifan Lokal”. Jurnal Studi Islam, vol. 9, no. 2, 2018.
9. Santoso, Purwadi. Islam dan Kearifan Lokal: Studi Kasus Tradisi Keislaman di Jawa”. Jurnal Al-Banjari, vol. 12, no. 1, 2017.
